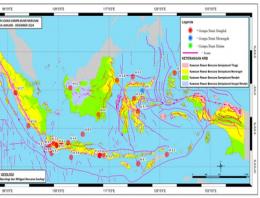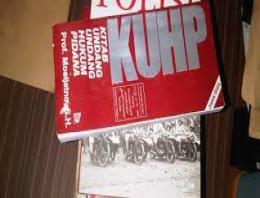Dari dulu hingga kini dan nanti, dunia adalah panggung sandiwara, tempat manusia berekspresi dan mengekspresikan diri. Lebih-lebih di era keterbukaan media, saat mana ruang-ruang informasi terpampang di depan mata, melekat di ujung jari. Segala bentuk ekspresi bisa dinaikkan ke panggung setiap saat untuk disiarkan, agar seluruh dunia tahu eksistensinya.
Di ruang ini, siapa pun bebas tampil, dan apa pun bisa ditampilkan. Tak peduli pantas atau tak pantas, berupa pujian atau cacian, sindiran atau blak-blakan, menyenangkan atau menyakitkan, asli atau palsu. Bebas. Telanjang.
Kita yang akrab dengan aplikasi media sosial, tentu tak asing dengan lambang- lambang emoji yang disediakan sebagai bagian dari program mengekspresikan emosi pengguna. Di sana ada lambang tawa, tangis, haru, cinta, marah, sedih, setuju, dan lain-lain. Lambang-lambang itu menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup kita berinteraksi di media sosial.
Di media sosial, kita lebih bebas untuk menyatakan emosi apa pun ketimbang di media konvensional maupun dalam interaksi nyata. Namun tak sedikit dari emosi yang ditayangkan di media sosial itu hanyalah ornamen periferal atau hiasan basa-basi—bukan kenyataan emosi yang sungguh-sungguh dirasakan.
Maka tak aneh—untuk tidak menyatakan wajar—jika media sosial menjadi ladang subur, tempat berseminya aneka kepalsuan alias hoax. Bibit informasi berkualitas yang kita tanam di ladang “media sosial” acap kali kalah bersaing dengan rumput-rumput yang juga tumbuh subur di sekelilingnya, yakni berupa berita-berita palsu. Jika kita tak sigap mengatasi rumput-rumput itu, bukan tak mungkin bibit asli yang kita tanam gagal tumbuh, atau tak berkembang.
Citra dan Pencitraan
Sistem sosial di era kebebasan dan keterbukaan informasi mendorong segala hal dipromosikan, diniagakan, dan dijajakan. Termasuk citra diri. Contoh paling aktual adalah mekanisme seleksi pemimpin publik. Popularitas menjadi kriteria utama—untuk tidak menyebut satu-satunya. Siapa mampu menjajakan dirinya ke khalayak luas, lalu meraih simpati publik dan mendulang popularitas, potensial menjadi pemimpin.
Calon pemimpin menjelma laiknya komoditas; dijajakan dan dipromosikan. Orang yang berhasrat menjadi pemimpin dituntut mampu menjajakan dirinya agar diterima oleh khalayak luas. Dalam sistem seperti ini, pencitraan menjadi tak terelakkan. Untuk itu, dibutuhkan strategi.
Secara sederhana, citra berarti gambaran. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan citra (dalam konteks manajemen) sebagai “gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk.” Orang yang citranya baik biasanya dipuji, didekati, bahkan dikerubungi. Orang yang citranya buruk akan dijauhi, dan tak jarang juga dicaci maki.
Dari kata “citra” terbentuk istilah “pencitraan.” Merupakan istilah yang pada dasarnya bermakna positif, namun kemudian memiliki konotasi negatif ketika dikaitkan dengan perilaku tertentu, seperti ria dan narsisme. Hal ini bisa terjadi dalam kancah sosial dengan tingkat kompetisi yang terus mengetat. Di sini, fakta, fitnah, asumsi, dan persepsi “berperang” untuk saling memengaruhi.
Dalam dunia pencitraan, kemasan menjadi panglima yang sangat menentukan tingkat keterpilihan seseorang di pasar sosial. Orang yang mampu mengemas dirinya untuk tampil paling baik di etalase-etalase media akan menarik simpati masyarakat. Untuk itu, segala macam kebaikan terkait dirinya ditampilkan ke permukaan, bahkan tak jarang dilebih-lebihkan.
Ria dan narsisme dilumrahkan demi membangun persepsi publik. Reputasi dan potensi ditonjol-tonjolkan. Janji-janji dan imaji muluk disodor-sodorkan. Alhasil, ruang sosial dipenuhi pamflet-pamflet norak dengan atraksi-atraksi profiling dan imaging. Pencitraan mengemas data dan fakta potensial dengan ornamen-ornamen fungsional. Di dalamnya, klaim dan apresiasi campur aduk.
Pencitraan bekerja mengemas potret diri dan memajang serta menjajakannya ke ruang publik, diikuti rangkaian puja-puji dan janji-janji yang melambungkan. Tak cukup dengan amunisi fakta, kadang fitnah, kebohongan, dan olok-olokan pun diramu sedemikian rupa. Di sini pencitraan menjelma tidak saja ria dan narsisme, tapi juga propaganda dosa tanpa rasa bersalah.
Tak ayal, klaim citra diri bersih (dan yang lain kotor) berkembang secara masif, meskipun tak jarang dalam realitas praktik sosial bercampur antara kebenaran dan dusta yang diada-adakan.
Propaganda
Menteri Propaganda Nazi di zaman kekuasaan Adolf Hitler, Jozef Goebbels pernah mengatakan, “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang akan membuat publik percaya.” “Dakwah” Goebbels ini seakan menemukan momentumnya di era kebebasan informasi seperti saat ini. Dia juga mengajarkan bahwa kebohongan paling besar ialah mengubah kebenaran sedikit saja.
Kini, hampir semua teknik propaganda yang pernah ada berkembang pesat. Teknik pemberian julukan (name calling), misalnya, sering digunakan media sosial maupun konvensional untuk menjatuhkan seseorang, kelompok, atau ideologi (kepercayaan) tertentu.
Berkembang pula teknik transfer, mengasosiasikan seseorang atau kelompok tertentu dengan sesuatu yang mempunyai kredibilitas baik atau buruk. Teknik tebang pilih (card stacking) dengan cara memilih data dan fakta tertentu yang dimunculkan ke permukaan untuk membangun persepsi positif atau negatif, sembari menyembunyikan fakta-fakta lainnya.
Propaganda digunakan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan. Kebenaran dimodifikasi sedemikian rupa sehingga nilai orisinalitasnya kabur dan menjadi tampak palsu. Sementara kepalsuan didandani dan dirias dengan apik sehingga memiliki kekuatan pesona dan menjadi tampak benar.
Konon, “ritual” memilih pemimpin dalam sistem demokrasi adalah perayaan, yang sering dinyatakan dengan “pesta demokrasi.” Layaknya sebuah pesta, dibutuhkan modal besar, kuali besar, juga nyali besar. Modal besar dibutuhkan untuk belanja tuak-tuak demokrasi, agar semua stakeholder dapat menikmati pesta dengan riang gembira. Hiruk pikuk kampanye adalah saat kemeriahan kolosal digelar dengan aneka hiburan memabukkan. Rakyat pun mabuk politik setelah menenggak tuak-tuak demokrasi. (*)
(Sumber : Hadiri Abdurrazaq -geotimes.id)