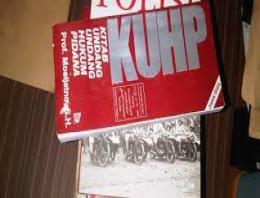Hari ini, selain kita tengah dilanda darurat pandemi covid, yang menyebabkan rumah sakit dan tenaga kesehatan keteteran. Juga ujian kematangan demokrasi terjadi. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM-UI) memposting di laman instagramnya meme Jokowi: The King of Lip Service.
Disimbolkan foto dan mahkota. Tidak lama kemudian, media, baik cetak, elektronik dan sosial, segera ramai memperdebatkannya. Tesis BEM-UI adalah kekecewaan pada Presiden Jokowi yang kerap tidak selaras antara kata dan perbuatan. Ada jarak melebar. Seperti ketika Presiden Jokowi merindukan di demo mahasiswa. Namun, ketika mahasiswa aksi mengalami represi. Begitu pula saat komitmen memperkuat KPK, lalu Undang-Undang KPK direvisi yang dinilai melemahkan pemberantasan korupsi.
Tentu, publik bisa berdebat soal itu. Kita negara demokrasi. Berbeda pendapat dan bertikai gagasan adalah lumrah. Dijamin di Pasal 28 UUD 1945. Kebebasan mengemukakan pendapat. Negara wajib memastikannya. Tentu dengan catatan, kebebasan dijamin baik sebelum, ketika dan sesudah kebebasan dilakukan. Sepanjang, bukan fitnah, pencemaran nama baik atau menghina orang lain. Itupun harus diselesaikan di pengadilan.
Tapi lebih dari itu, saya hendak mengupas lebih dalam. Soal adanya komorbid dalam demokrasi kita. Penyakit bawaan yang bisa berpotensi memperparah kualitas demokrasi manakala ada terjangan polemik. Atau serangan pandemi yang mau tidak mau harus menyediakan wahana isolasi agar demokrasi tetap berjalan tanpa mengorbankan penanganan pandemi.
Lokus Komorbid Demokrasi
Mari kita main data, supaya tidak dituduh bodoh atau tidak argumentatif. Badan Pusat Statistik (BPS) mengemukakan tingkat pendidikan penduduk Indonesia umumnya hanya mencapai pendidikan menengah. Data Susenas 2019 menunjukkan bahwa hanya satu dari empat penduduk 15 tahun ke atas telah tamat Sekolah Menengah/SM/sederajat, dan hanya sekitar sembilan persen yang berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang Perguruan Tinggi (PT). Persentase penduduk di pedesaan tidak pernah sekolah dan tidak tamat Sekolah Dasar lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di pedesaan sebagian besar hanya tamatan Sekolah Dasar (31,77 persen). Sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SM/sederajat (33,13 persen). Status ekonomi masih membedakan capaian tingkat pendidikan penduduk. Semakin tinggi status ekonomi penduduk, semakin tinggi jenjang pendidikan yang dapat diselesaikan. Belum lagi pandemi covid yang diduga akan berdampak pada angka putus sekolah.
Fakta diatas dipersuram dengan kondisi literasi. Penelitian UNESCO tahun 2016 terhadap 61 negara termasuk Indonesia menunjukan budaya membaca kita rendah. Indonesia diperingkat ke-60 hanya satu tingkat di atas Botswana. Ada masalah di akses membaca, berdasarkan survey Kemendikbud di angka 23,09 persen. Berkorelasi dengan dimensi budaya yang rendah sebesar 28,50 persen. Ini wajar jika akses rendah, budaya literasi susah tumbuh. (https://edukasi.kompas.com/read/2019/06/23/07015701/literasi-baca-indonesia-rendah-akses-baca-diduga-jadi-penyebab).
Paradoks dari rendah literasi dan tingkat pendidikan, di sisi lain, Indonesia dinobatkan pengguna teraktif facebook nomor tiga di dunia, sebesar 140 juta. Di bawah Amerika Serikat 240 juta dan India paling tinggi, 270 juta (https://www.liputan6.com/tekno/read/3481323/5-negara-dengan-jumlah-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-berapa). Ini paradoks yang berdampak ke pelbagai hal.
Bagi saya, data di atas di mana aktif media sosial terbesar nomer tiga sementara literasi membaca rendah dan pendidikan secara umum tidak merata dan didominasi pendidikan menengah, itupun di perkotaan, berakibat serius sebagai komorbid demokrasi. Apa implikasinya. Pertama, menjamurnya industri hoax sebagai bagian era post-truth dengan sangat luar biasa ganasnya. Kedua, banyaknya penipuan berbasis online dan banyak korbannya di ruang publik dengan marak. Ketiga, banyaknya sebagian pihak terkaget kaget oleh kritik. Kebebasan berbicara. Debat di televisi yang marak. Perang buzzer (pendengung). Serta sukarnya mengendalikan opini publik. Tentu tugas berat negara adalah memastikan tidak “tipis” kuping terhadap kritik dan menghindari godaan represi sebagai jalan pintasnya. Kita pernah punya pengalaman buruk Orde Baru (Orba) akibat keteledoran merawat mutu demokrasi. Keempat, ujungnya indeks demokrasi kita tertinggal. Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020, kita berada di peringkat ke-64 dunia dengan skor 6,3, menurun skornya dari sebelumnya 6,48.Ini merupakan angka terendah dalam 14 tahun terakhir sehingga Indonesia dikategorikan sebagai demokrasi cacat. Menjamurnya politik uang dan politik identitas turut berkontribusi pada turunnya mutu demokrasi.
Peran Mahasiswa
Di dalam perspektif saya, Presiden Jokowi nampaknya memahami hal di atas. Dalam pidatonya ketika mendapat kritik oleh BEM-UI ditanggapi dengan biasa dan sederhana sebagai konsekuensi demokrasi. Hanya presiden mengingatkan soal tatakrama dalam berpendapat.
Tentu wilayah tatakrama merupakan ranah subyektif dan dapat dipolemikan. Tergantung perspektif dan paradigma memandang suatu peristiwa. Bisa jadi satu pihak menilai sesuatu hal sopan. Namun pihak lain tidak. Hanya karena perbedaan kultur dan referensi. Bagi saya, rambu rambu lebih terukur adalah hukum. Selama bukan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perundang-undangan lain terkait maka selebihnya sudah sepatutnya dianggap bunga demokrasi. Tentu UU ITE perlu dikaji dan jika perlu direvisi sepanjang hasil kajian obyektif melihat adanya norma yang berpotensi membahayakan demokrasi. Demikian pula sisi lain, kepolisian sebagai penegak hukum---yang disumpah dalam profesinya---wajib menegakan hukum dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Konteks ini yang dapat kita pahami dari kebijakan Kapolri soal pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik. Agar tidak ada kriminalisasi dalam demokrasi.
Bagi saya, di setiap zaman, mahasiswa adalah alarm peradaban negara. Semua perubahan, entah itu revolusi maupun reformasi, selalu motornya mahasiswa. Meski mahasiswa---seperti film holywood---sering terakhir berbunyi, namun setidaknya bisa menjadi cermin bagi publik. Bagi saya, kerasnya kritik mahasiswa, dikontribusi pula lemahnya parlemen merepresentasikan suara dan nurani masyarakat di ruang publik. Nyaris jarang melihat dan terdengar kritik berbobot parlemen pada pemerintah sebagai mitra dalam konteks demokrasi. Ini pekerjaan rumah yang mendesak diperbaiki.
Pada akhirnya, memperbaiki demokrasi harus dengan terlebih dahulu membenahi komorbid demokrasi berupa perbaikan kualitas pendidikan, literasi dan optimalisasi jaminan suara kritis dilembagakan. Tanpa itu, seperti efek covid pada penderita komorbid yang sering mematikan. Maka demokrasi pun bisa mengalami hal sama. Memperbaiki komorbid demokrasi berarti menyelamatkan peradaban bangsa.
(Penulis : Kepala Pusat Unggulan Konstitusi dan HAM, FH Universitas Pakuan, R Muhammad Mihradi, SH, MH)