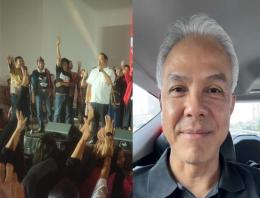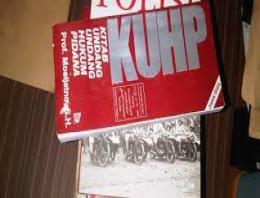”Sampai pada waktu-waktu yang terakhir, hampir ada kita memikirkan pendidikan kecerdasan dan penyempurnaan akal budi pekerti bangsa Bumiputera. Asal pajak dibayarkan, kewajiban rodi dan bertanam dilakukannya, asal kehidupan rakyat tidak sengsara, memadailah. Maka senanglah hati pemerintah.”
(Van Deventer dalam majalah De Gids, 1908).
Pendidikan formal mulai hadir di Indonesia pada awal 20 (pemberlakuan Politik Etis : 1900-1942) ketika kolonialis Belanda mengeluarkan kebijakan Politik Etis. Hadirnya pendidikan di negeri Indonesia yang terjajah saat itu, sebetulnya merupakan buah dari desakan perubahan politik dagang kolonial yang bersifat monopolistik menjadi politik kapital dagang industri yang bersifat persaingan bebas, sebagai akibat tuntutan swastanisasi dari borjuis–borjuis yang sedang berkembang di negara tersebut. Pengusaha–pengusaha Belanda yang masuk ke Indonesia tersebut mengalami problem tenaga kerja secara fundamental, yaitu lemahnya tenaga produktif di Indonesia. Maka mulailah muncul sekolah–sekolah walaupun masih diskriminatif dalam penerimaan siswanya. Bagi pemerintahan Belanda, Politik Etis merupakan politik balas jasa terhadap negara jajahannya, Indonesia.
Melalui pendidikan tersebut, pihak kolonial mengharapkan terciptanya tenaga kerja–tenaga kerja terdidik sesuai dengan keinginan laju ekspansi modal swasta dari Belanda. Pendidikan dalam Politik Etis memiliki kepentingan untuk mencetak tenaga administrasi rendahan dari golongan pribumi yang mampu menggantikan posisi tenaga kerja dari negeri Belanda. Dengan demikian biaya lebih murah akan menjadi keunggulan komparatifnya.
Tujuan dari sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda adalah guna menghasilkan tenaga birokrat (sesuai dengan jenjang pendidikannya) mengisi jabatan-jabatan teknis, pos-pos administrasi didalam pabrik-pabrik maupun perkebunan milik pemerintah kolonial Belanda sejak terjadinya sistem Tanam Paksa.
Tahun 1900 berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa. Pada tahun 1903 mulai didirikan sekolah rendah yang dinamakan Volk School (Sekolah Desa) dengan masa belajar 3 tahun yang kemudian dilanjutkan dengan program Vervolg School (Sekolah Lanjutan) dengan masa belajar selama 2 tahun. Sekolah semacam ini lalu dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya, misalnya Meer Uitgebreid Leger Onderwijs (MULO), yakni sebuah sekolah yang jenjangnya setingkat dengan SMP dan Algemeene Middelbare School (AMS) yang jenjangnya setingkat dengan SMA, Eerste Klass Inlandsche (sekolah bumiputera angka satu) untuk anak-anak priayi dan orang-orang ”berada”, serta Tweede Klass Inlandsche Scholen (sekolah bumiputera angka dua) bagi anak-anak rakyat kebanyakan. Selain itu berdiri pula sekolah-sekolah lanjutan seperti Hollandsche Inlandsche School (HIS), Hollandsche Burgerscholen (HBS),
School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA). Dalam prakteknya sekolah-sekolah tersebut sangatlah diskriminatif, termasuk dalam hal penerimaan peserta didik. Selain memberlakukan biaya sekolah yang cukup mahal, sekolah yang ada hanya diperuntukkan bagi kalangan ningrat-bangsawan atau dari kalangan para “priyayi” (pangreh praja atau pegawai dalam kantor pemerintah Belanda). Bagi rakyat biasa terpaksa tidak dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah tersebut, atau paling tidak terpaksa mengambil alternatif lain, misalnya memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren.
Obor Pencerahan Kaum Bumiputera!
Namun, bagai pisau bermata dua, pendidikan dalam Politik Etis tersebut justru menjadi bumerang bagi kelangsungan penjajahan Belanda sendiri. Dalam perkembangannya, keberadaan (sekolah) pendidikan tersebut membawa perubahan pada negeri jajahan. Kemajuan yang diperoleh melalui pendidikan dalam Politik Etis di negeri jajahan akhirnya mampu membuka tabir penindasan yang dialami oleh bangsanya. Melalui pengetahuan baru yang dimilikinya, kalangan pribumi mampu membaca dan mempelajari buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Buku-buku ini membuka kesadaran baru tentang perjuangan pembebasan nasional di seluruh negeri di bumi ini.
Pendirian perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 1945 dimulai dengan dibentuknya Badan Perguruan Tinggi Republik Indonesia (BPTRI) di Jakarta. Namun keberadaannya sempat berpindah sementara (dipindahkan ke Klaten) oleh karena Agresi Militer Belanda pada akhir 1945. Akhirnya, setelah Jakarta kembali berhasil diambil alih pada awal 1950, pemerintah mengembalikan BPTRI ke Jakarta dan menggabungkannya dengan Unibersiteit van Indonesie, dan memberinya nama baru Universiteit Indonesia (UI). Selain itu, pada 19 Desember 1949 pemerintah Indonesia telah mendirikan Universitas Gajah Mada (UGM).
Paska itu, pada 10 November 1954, Bung Karno melakukan nasionalisasi terhadap Nederlands Indische Artsen School (NIAS) dan School Tot Opleeiding van Indishe Tandartsen (STOVIT), yang masing-masing didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1913 dan 1928, menjadi Universitas Airlangga di Surabaya. Jika diteliti dari sejarahnya, kelahiran universitas di Indonesia adalah lahir dari penderitaan dan perjuangan rakyat, dimana ”ia” lahir dari jantung perjuangan rakyat melawan penindasan kolonialisme pemerintah Belanda, yang adalah sebagai sebuah anti-tesis pergolakan sosial-politik akibat kolonialime awal abad ke-20 saat revolusi kemerdekaan Indonesia. (Kompas, 20 Juli 2011)
Jejak Lahirnya Neo-Liberalisme Pada Pendidikan Nasional
Situasi sekarang justru berbeda, ditengah jerat sistem kapitalis-imperialis. Paska 1965, seiring dengan kekuasaan ekonomi-politik rejim Orde Baru-Soeharto, modal asing (AS, Kanada, Inggris, Jepang, dll) gencar masuk ke Indonesia. Oleh karenanya modal asing tersebut membutuhkan instrument pendukung guna mengembangankan kapital industri di Indonesia. Industrialisasi asing ini sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil terdidik lulusan-lulusan perguruan-perguruan tinggi.
Maka seketika itu pendidikan tinggi menjadi lahan industri strategis yang berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara kapitalis-imperialis, dengan mencetak tenaga-tenaga kerja bagi perusahaan-perusahaan swasta. Pendidikan menjadi komoditi utama bagi akumulasi keuntungan (modal).
Liberalisme Pendidikan Indonesia Di Era Kapitalisme-Neoliberal!
Setelah Indonesia masuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 1994 melalui disahkannya UU nomor 7 tahun 1994, jasa pendidikan merupakan bagian dari jasa yang harus diliberalisasi (kurangi subsidinya). Salah satu tujuan dari Pertemuan Tingkat Menteri dari 125 negara di Uruguay pada tahun 1993 adalah memperluas cakupan produk perdagangan internasional, termasuk perdagangan dibidang jasa, pengaturan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan.
Sehingga tidak heran bagi rakyat Indonesia jika paska masuknya Indonesia menjadi anggota WTO ini, berangsur-angsur subsidi sosial dicabut dan privatisasi aset-aset vital negara mulai dilakukan secara masif.
Hak dasar pendidikan sulit dipenuhi
Paska Reformasi 1998, formulasi arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta dalam UUD 45 pasal 31 ayat 4 menegaskan supaya negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurang nya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah agar memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. (*Penulis : Herdiyatna, Sekretaris BEM Unpak 2016-2017)